Di tengah carut marutnya manajemen pendidikan tanah air, saya menemukan sebuah oase. Oase itu menamakan dirinya: Anane 29 (Anane Sangalikur). Mereka adalah para alumni sebuah sanggar belajar yang kerap disebut SALAM, Sanggar Anak Alam. SALAM yang diinisiasi dan tekun diasuh oleh Sri Wahyaningsih (bu Wahya) ini aktif berkegiatan di desa Lawen, Pandanarum, Banjarnegara pada medio 1988-1996.
Tentang Lawen dan Anane 29 ini sudah kerap saya dengar sebelumnya lewat cerita-cerita tutur dari bu Wahya dan lewat buku: Sekolah Biasa Saja karya pak Toto Rahardjo. Tapi untuk berkunjung kesana, dan berjumpa langsung dengan mereka bukanlah sebuah ambisi. Hanya seperti semilir angin sepoi-sepoi yang berlalu begitu saja.

Hingga suatu hari, bu Wahya mengajak saya dan beberapa orangtua secara personal untuk berkunjung langsung dan membantu mencari solusi untuk beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman di Lawen. Tentu saja ini bukan ajakan yang mudah diiyakan, semudah menanggapi ajakan garage sale atau karaokean sore-sore seperti yang sering kami, orangtua SALAM Jogja, lakukan. Ajakan ini butuh pemikiran, pemahaman dan waktu yang tidak sedikit mengingat jarak Lawen-Jogja tercepat adalah 6 jam berkendara. Jika tidak diagendakan secara cermat, kegiatan serupa anjangsana ini mudah sekali gagal oleh rasa malas.
Benar saja. Dari sekian orangtua yang saya jawil, hanya satu yang luang waktunya di tanggal yang teragendakan. Ya sudahlah. Rencana harus tetap berjalan. Berbekal ketidaktahuan dan sedikit prolog yang terulang dari cerita-cerita tutur bu Wahya, kami berangkat. Bukan formasi yang brilian pula karena hanya ada saya dan suami yang sedikit berpengalaman di bidang bisnis produk kreatif, pak David yang pegiat literasi di Rumah Baca Komunitas, Bu Wahya sang sesepuh, mas Nano yang menguasai medan jalur Jogja-Lawen, dan dua orang balita: anak saya, Jalu dan cucu bu Wahya, Sandhi yang menguasai ruang bicara selama mereka terbangun dalam perjalanan.
Kami berangkat pada Jumat siang, selepas pukul dua. Jalur yang ditempuh juga bukan jalur konvensional layaknya saran GPS. Kami memintas Jogja lewat rute Godean-Sembuhan-Dekso dan melepas Jogja lewat perbatasan Kulon Progo-Magelang. Melintas Borobudur dan Wonosobo untuk mencapai Banjarnegara. Setelahnya hanya mas Nano dan Tuhan yang tahu jalur mana saja yang kami lewati untuk sampai di Lawen pada pukul 20.20. Saya yakin banyak pemandangan menarik yang saya lewatkan karena rute Banjarnegara kota menuju Lawen terlintas naik dan turun tepat setelah matahari membenamkan diri.
Lawen menyambut kami dengan bersahabat. Terbukti hawa dingin yang kami rasakan malam itu tidak semencekam yang saya bayangkan. Kami menginap di rumah leluhur pak Toto, persis di seberang bangunan yang dulunya ‘gedung sekolah’ Salam. Setelah para balita terkondisikan dengan baik di atas kasur masing-masing, kami pun mulai berbincang sambil menyantap ondol dan menyeruput kopi.
Esok paginya, kami mengawali hari dengan melihat langsung bangunan yang bagi kami, komunitas SALAM, bak cagar budaya. Sang Gedung Sekolah yang arsitekturnya dibesut sendiri oleh arsitek paling humanis, Romo Mangun, itu masih menyisakan kecantikan nan fotogenik meskipun banyak kerusakan dimana-mana. Derita yang ditanggungnya karena longsor beberapa waktu yang lalu, ditambah minimnya sentuhan manusia di masa-masa terakhir, menjadikannya serupa bangunan odd stad yang meraung memohon revitalisasi.
Setelah menyantap sarapan, beberapa butir ondol dan secangkir kopi, seorang kawan dari komunitas Anane 29 datang. Mas Udin, namanya. Mas Udin termasuk generasi akhir dari SALAM Lawen. Sempat kuliah pertanian dan beberapa tahun menjadi fasilitator di SALAM Jogja. Setelah berbicang sedikit tentang rencana pertemuan malam nanti, kami pun dipandunya menyusuri desa dengan berjalan kaki untuk menuju sungai. Para balita begitu bersemangat dengan aksi susur sungai ini. Jalu bahkan sudah menguasai teknik ‘ngintir’ jika menemukan bagian-bagian sungai berkedalaman setinggi betis orang dewasa. Belakangan, Sandhi menemukan teknik yang sama hingga memerlukan segudang rasa lelah dan sedikit paksaan untuk membuatnya mentas.
Kami sempat berbincang panjang dengan alumni lain, mas Yanto, sesudah petualangan kecil itu. Rumah tinggalnya hanya selemparan batu dari tempat kami menginap. Hanya dengan melihat sekilas saya tahu, bahwa rumah mas Yanto ini penuh daya artistik. Berdinding bata ekspos dan memanfaatkan perbedaan ketinggian jalan, rumah ini menunjukkan bahwa pemilik sekaligus arsiteknya adalah seorang pembelajar.

Benar saja. Ketika saya berkesempatan untuk ‘menjelajah’ ke dalam, banyak hal terkait kegigihan belajar yang tercermin pada elemen-elemen ruang. Seperti tangga yang tampak curam namun tetap nyaman untuk dilewati, void di atas tangga yang bermandikan cahaya, dapur ramping khas rumah perkotaan dengan pantry menghadap ruang keluarga, lampu tanam pada kusen-kusen jendela dan zoning yang terkelola baik bukanlah ilmu yang mudah didapat apalagi diaplikasikan begitu saja.
Di lantai atas, tepat di sisi bangunan yang terbuka menghadap jalan, adalah bengkel kayu tempat mas Yanto berkarya sehari-harinya. Belasan batang kayu mahoni dalam berbagai bentuk sudut dan ukuran tersusun rapi di beberapa sudut ruang. Mereka adalah bagian-bagian dari projek yang sedang dikerjakan mas Yanto: meja rendah untuk TPA Masjid Lawen yang dibuat dengan teknik knock down. Bagi saya yang (gayanya) pernah mengikuti mata kuliah desain mebel, teknik knock down bukanlah sebuah teknik yang mudah diterapkan. Apalagi jika fungsinya sekedar meja TPA, teknik knock down terdengar berlebihan. Tapi mas Yanto merancang dan membuatnya dengan senang hati. Entah kenapa, saya menemukan kilasan senyum Romo Mangun dalam penjelajahan kecil ini.
Selepas itu adalah sebuah jeda hari yang terasa begitu panjang dan membosankan untuk menuju pertemuan yang dijadwalkan pukul 7 malam. Kami bahkan sempat tidur siang, ngopi, makan lagi dan ngopi lagi entah untuk kali yang keberapa. Sulitnya sinyal di Lawen juga sedikit banyak ikut andil dalam tingginya tingkat kebosanan yang saya alami.
***
Meski diiringi dengan guyuran hujan, tapi pertemuan malam itu dimulai tepat waktu. Teman-teman dari komunitas Anane 29 berkumpul dalam formasi yang cukup lengkap. Selain mas Udin dan mas Yanto yang sudah kami temui sebelumnya, kami bertemu dengan para alumni angkatan pertama diantaranya mas Marsum, mas Benny,mas Tarsono, mas Slamet, Eman dan beberapa alumni angkatan paling akhir seperti Bayu dan Udin. Beberapa diantara mereka tidak begitu saya ingat nama dan angkatannya. Ada juga anggota komunitas yang bukan alumni SALAM, seperti mas Wawan, yang aktif terlibat justru setelah SALAM hijrah ke Jogja.
Awalnya saya membayangkan akan bertemu dengan pemuda-pemuda berusia pertengahan duapuluhan. Tapi ketika berhitung kembali, jika di medio tahun 1988 mereka berusia 5-10 tahun, maka yang saya jumpai adalah sebagian besar bapak-bapak yang mungkin berada di rentang usia 30-40 tahun, rentang usia yang tak jauh berbeda dengan kami, para orangtua yang menyekolahkan anaknya di SALAM, Nitiprayan. Dan disinilah kami, para sebaya dalam sebuah ruang komunitas yang sama, dalam keprihatinan yang sewarna di jarak habitat yang 6 jam jauhnya.

Pertemuan malam itu dipandu oleh mas Benny yang saat ini berprofesi sebagai guru kelas 6 SD negeri Lawen. Seperti yang telah mereka janjikan sebelumnya, beberapa materi telah dipersiapkan sebagai bahan diskusi, diantaranya profil sebuah Kelompok Usaha Bersama dan sebuah rencana anggaran biaya renovasi bangunan sekolah SALAM. Dalam suasana cair, mas Benny pun mulai berkisah tentang siapa dan apa saja harapan komunitas ini di masa mendatang.
Seperti terkisah sebelumnya, Anane 29 adalah para alumni SALAM Lawen yang rutin berkumpul dan berdiskusi tentang beragam keprihatinan di sekitar mereka. Dalam laku olah rasa ini, mereka bergerak sebagai katalis dan merakit sejumlah upaya untuk membuat tindakan nyata.
Meski banyak dari mereka yang pernah merantau baik untuk menimba ilmu atau bekerja, tapi olah rasa yang tumbuh dalam kebersamaan mereka selama berkegiatan di SALAM Lawen membuat mereka membulatkan sebuah tekat untuk kembali pulang dan membangun desa. Sungguh terdengar seperti jargon kampanye Pilkada, bukan? Bedanya, ini bukan jargon. Ini sebuah niat yang muncul sendiri dari para pembelajar ini, yang disampaikan dengan nyala dalam tatapan mata mereka.
Dengan beragam ketrampilan yang mereka miliki, mulai dari ketrampilan mengolah kayu, sablon dan cetak, bercocok tanam, hingga budidaya ikan, mereka meggabungkan diri menjadi sebuah Kelompok Usaha Bersama dengan bendera Agro Lestari. Dalam lampiran profil KUB mereka turut menyertakan SK Kemenkumham sebagai materi legalitas.
Mimpi mereka sederhana, membawa pulang kembali semangat SALAMyang dulu mereka alami dan mewariskannya kepada generasi yang lebih muda. Mereka juga sadar penuh, bahwa untuk saat ini, hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menggalang kegiatan yang bernilai ekonomi karena idealisme dan pemikiran kritis saja tidak cukup untuk membangun sebuah desa. Beberapa langkah konkrit yang akan mereka kerjakan adalah merenovasi kembali bangunan SALAM yang terbengkalai untuk ditata ulang sebagai pusat belajar, perpustakaan dan workshop kerja.
Diskusi malam itu bergulir ringan dan cepat. Begitu banyak ide, harapan, mimpi dan cita-cita yang saya serap malam itu. Dan entah bagaimana, saya merasakan energi positif memenuhi ruangan. Berkali-kali saya takjub, bagaimana sebuah desa seperti Lawen bisa melahirkan sebuah generasi yang begitu kritis dan giat. Lawen bukanlah desa yang dimanja oleh infrastruktur. Di medio 1988-1996 saja orang masih harus berjalan kaki sejauh 12 km melewati hutan pinus dengan medan naik turun khas dataran tinggi untuk menuju Kalibening, tempat terdekat untuk segala akses transportasi dan komunikasi. Listrik pertama kali menjamah Lawen di awal tahun 2000. Bahkan aspal yang mengantar kami menuju desa bisa dibilang masih hangat.

Dengan segala ketakjuban, saya dengan bangga menyimpulkan bahwa kami, para orangtua generasi milenial yang tumbuh di kota, adalah sesungguh-sungguhnya anak manja. Keberuntungan kami hanyalah sejauh aksesbilitas terhadap infrastruktur. Sialnya, kami jauh dari pola asuh pendidikan kritis yang penuh kreatifitas dan daya hidup. Wajar jika kami pintar sekali menulis sepanjang-panjangnya di dinding-dinding media sosial, tapi bodoh sekali ketika harus melakukan sependek-pendeknya kerja nyata.
***
Minggu pagi tiba. Setelah menyempatkan berbelanja di pasar Wage, saya kembali bertemu dengan teman-teman Anane 29. Mereka kembali berkumpul pagi itu untuk bergotong royong membersihkan bangunan sekolah dan merubuhkan dinding-dinding yang berpotensi rubuh. Meski rencana anggaran biaya renovasi belum pula beredar lebih jauh dari jangkauan tangan saya, tapi semangat mereka menguar jauh di udara. Siangnya kami berkemas untuk pulang. Semangat adalah sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana saat itu. Semoga semangat itu, semangat saya untuk membantu dan semangat teman-teman Lawen untuk berkarya, tidak ikut terkemas setelahnya. Karena bila bung Karno pernah meminta 10 pemuda untuk mengguncang dunia, maka selayaknya merekalah yang akan saya sodorkan pada beliau.
Kali ini kami pulang lewat jalur yang berbeda selepas Kalibening untuk menghindari kemacetan karena perbaikan jalan. Teduh warna hijau daun pinus dan aroma gunung melepas kami pulang. Apa yang mata saya tangkap sepanjang Lawen- Banjarnegara memberi saya sebuah ide tentang alasan Tuhan menciptakan SALAM di Lawen: karena hanya manusialah yang paling bisa menjauhkan bumi dari keserakahan.
Orang Tua Murid SALAM
Orang Tua Murid & Fasilitator SMA SALAM

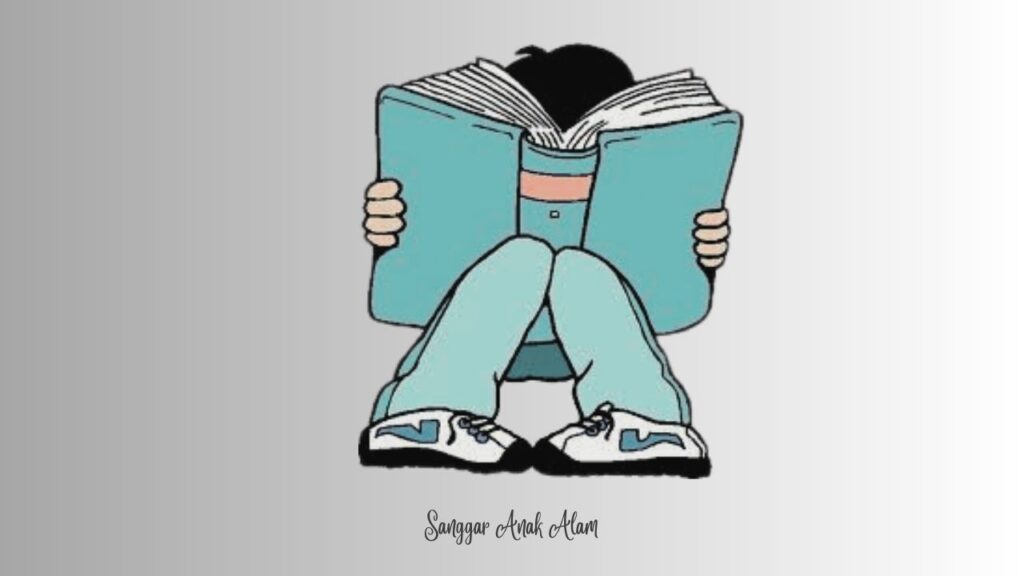

Leave a Reply