Hari Sabtu yang terlalu cerah, seperti senyum yang sedikit berlebihan di wajah kota yang sedang menutupi luka. Di sudut lain Yogyakarta, di halaman luas Hotel Sheraton Mustika yang berpendingin udara sampai ke akar daun, anak-anak dari kelas minat masak berdiri kikuk. Mereka membawa bahan-bahan dari pasar: pisang kepok kuning, santan segar, telur, gula, dan sejumput garam yang belum tentu murni tapi jujur. Di tangan kecil mereka, Carang Gesing bukan sekadar kudapan manis, melainkan cara paling sederhana untuk menyapa dunia yang mulai lupa bau dapur kayu.
Jogja Cultural Wellness Festival, nama yang panjang dan hangat diucapkan, adalah sebuah pesta tahunan yang katanya merayakan “keseimbangan dan kebahagiaan”. Di sana, tubuh-tubuh dilatih bernapas, pikiran dibersihkan, dan makanan dikatakan sebagai jalan menuju ketenangan batin. Tapi bukankah di kota ini, keseimbangan justru sering dibeli dengan ketimpangan? Sementara di ruang berpendingin itu, anak-anak belajar membungkus Carang Gesing dengan daun pisang—di luar sana, para petani pisang masih menimbang harga hasil panennya di bawah payung rusak di pasar subuh.

Anak-anak tertawa ketika keju parut mereka jatuh ke lantai rerumputan. Mereka tak sadar sedang menciptakan puisi kecil tentang pertemuan dua dunia: keju dari negeri jauh yang disandingkan dengan pisang dari kebun tetangga. Inilah bentuk paling polos dari globalisasi: rasa ingin tahu yang belum tercemar ambisi.
Kami, para pendamping, hanya bisa memandang dengan bangga sekaligus getir. Karena kami tahu, di balik setiap lembar daun pembungkus Carang Gesing, terselip harapan agar mereka kelak tak kehilangan arah di tengah aroma harum modernitas. Bahwa dari dapur kecil itu, anak-anak belajar tentang kedaulatan pangan—kata yang terlalu besar, tapi sejatinya bermula dari keberanian mengolah apa yang tumbuh di tanah sendiri.
Ketika festival berakhir, para tamu hotel bertepuk tangan sopan, menilai rasa dan presentasi dengan senyum diplomatis. Tapi bagi kami, kemenangan sesungguhnya bukan pada pujian itu, melainkan pada momen ketika seorang anak berkata lirih, “Daunnya wangi, ya, Bu. Kalau panas, jadi lembut, kayak rumah.”
Kalimat itu lebih berharga dari semua sertifikat. Karena di dalamnya ada ingatan—tentang rumah, tentang tanah, tentang masa depan yang tidak diukur dari kemewahan hotel, tapi dari kemampuan menjaga kemanusiaan di tengah kerapuhan dunia—begitulah seharusnya demokrasi: seperti Carang Gesing. Terbungkus sederhana, di dalamnya bercampur manis, gurih, dan asin kehidupan. Semua rasa ada tempatnya, asal tidak ada yang dilupakan.
Hari itu, Sabtu yang cerah terlalu riang. Langit Yogyakarta seperti tersenyum lebar, tapi di dalam dada kami berempat—para mentor kelas minat masak—ada kegelisahan kecil yang mengintip dari balik celemek. Kami akan memasak di luar ruangan, di halaman luas Hotel Sheraton Mustika, tempat rumputnya dipangkas seragam dan angin terasa seperti disaring dari segala kemungkinan bau dapur. Ini pengalaman pertama kami dan anak-anak memasak di luar jam kegiatan reguler—sebuah petualangan kecil yang ternyata segera berubah menjadi ujian kesabaran.
Gas 3 kilogram yang dibawa bapak yang antar anak-anak ternyata kehilangan sesuatu yang sederhana tapi menentukan nasib: sill karet. Sehelai cincin kecil yang membuat api bisa menyala dan harapan tetap hidup. Kami sudah menyiapkan santan, telur, gula, dan pisang—tapi tidak sepotong karet itu. Kami mencoba meminjam pada teknisi hotel yang terbiasa menghadapi kebocoran kelas bintang lima, tapi bahkan alat mereka menyerah di hadapan tabung kecil kami yang rewel.
Kami berdiri dengan harapan setipis tisu di meja prasmanan. Beberapa dari kami mencoba menelpon orang tua anak-anak, berharap ada yang masih dalam perjalanan dan bisa membeli sill karet di warung. Dan ketika akhirnya satu ibu datang membawa benda mungil itu, kami seperti baru saja diselamatkan dari kehampaan. Api menyala, kukusan berdiri tegak, dan dunia kembali berputar.
Di sela ketegangan itu, kami mengajak anak-anak membuat takir—wadah dari daun pisang yang sudah lama tersingkir oleh plastik dan styrofoam.
“Aduh, sobek, Bu!”
“Bu, susah banget, Bu!”
“Halah, aku nggak bisa!”
Begitulah orkestra kecil itu dimulai. Suara rengekan dan tawa bersahut-sahutan. Ada yang tekun, ada yang menyerah sebelum mencoba. Tapi ketika semua tangan kecil itu akhirnya memegang takir buatan sendiri, wajah mereka berubah: ada cahaya kecil di sana—kebanggaan yang tidak bisa dibeli dari rak minimarket mana pun.
“Siapa yang mau motong pisang, siapa yang motong keju?” tanya kami.
“Aku! Aku! Aku!” seru mereka serentak, seolah sedang memperebutkan jabatan penting dalam kabinet dapur. Kami membagi mereka dalam kelompok: tim pisang dan tim keju. Pisau tumpul di tangan mereka bergerak dengan kesungguhan yang tak kalah dari chef profesional. Setelah tugas selesai, sebagian anak bubar bermain—karena di dunia mereka, selesai bekerja berarti saatnya bersenang-senang.
Saat membuat adonan, beberapa anak menghitung telur dan gula dengan cermat.
“Aku nggak mau, Bu, nanti tanganku amis!”
“Enggak kok, sini, aku ajarin biar nggak kena tangan,” sahut temannya.
Dan di situlah pelajaran sebenarnya dimulai. Bukan tentang resep, tapi tentang keberanian mencoba, solidaritas kecil, dan kesediaan belajar dari teman.
Ketika aroma pandan mulai menari di udara, beberapa anak berlari menghampiri:
“Bu, udah mateng belum?”
Kami tertawa. Waktu memang tak pernah sabar di dunia anak-anak. Mereka mengantri sambil membawa takir hasil karya masing-masing. Takir-takir itu diisi Carang Gesing yang masih hangat, lembut, dan harum. Takir yang tadi mereka anggap remeh kini menjadi wadah kebanggaan—dan mungkin, simbol kecil tentang kemandirian.
Kami menutup kegiatan dengan segelas jus mangga untuk setiap anak. Tapi sesungguhnya, hadiah hari itu bukan jus, bukan pula Carang Gesing. Hadiahnya adalah pelajaran: bahwa api tidak selalu menyala dengan mudah, bahwa kesabaran bisa tumbuh dari kesalahan kecil, dan bahwa daun pisang masih bisa mengajarkan lebih banyak tentang hidup daripada brosur festival yang dicetak berwarna.
Di tengah festival yang gemerlap, anak-anak ini membawa sesuatu yang lebih murni dari semua slogan “wellness” dan “sustainability”: ketulusan bermain dan belajar. Mereka tak tahu apa itu demokrasi partisipatif, tapi tanpa sadar mereka mempraktikkannya—setiap kali memberi ruang bagi temannya untuk memecahkan telur, atau ketika membagi Carang Gesing secukupnya agar semua kebagian.
Mungkin begitulah seharusnya keadilan dan kemanusiaan dirayakan—tidak di ruang rapat, tapi di dapur sederhana yang nyaris tak menyala, di bawah langit yang terlalu cerah, di tangan-tangan kecil yang percaya bahwa setiap rasa punya tempatnya.[]
SALAM (Sanggar Anak Alam), Laboratorium Pendidikan Dasar, berdiri pada tahun 1988 di Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara.


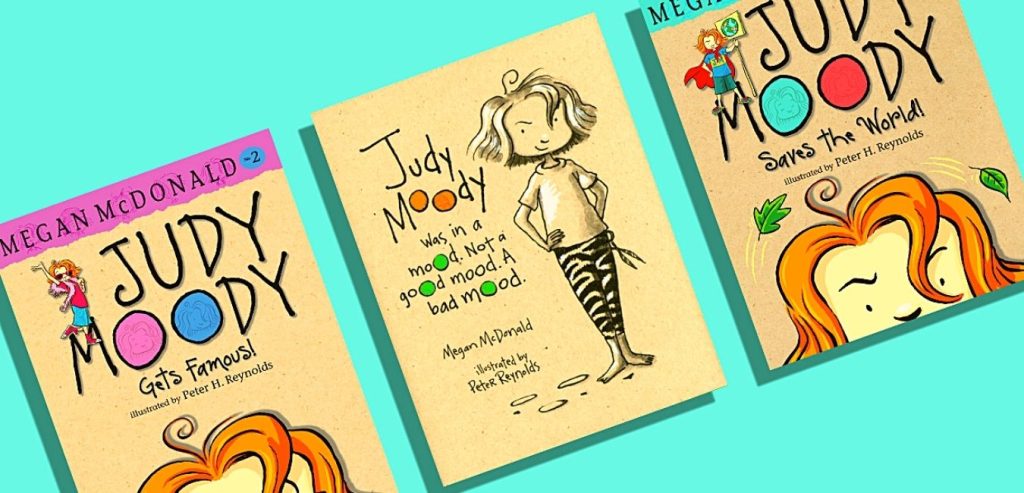
Leave a Reply